 (MI/Duta)
(MI/Duta)
BETAWI ialah sebuah agregat. Ia diceritakan dengan sangat apik pada sebuah Sabtu di halaman Sekolah Kanisius, Menteng, Jakarta. Ratusan siswa berdandan aneka busana adat. Dari lapangan yang luas, riuh suara musik menyatu dengan langkah kaki gemuruh. Sebuah teater kolosal dipersembahkan: Batavia Ethnica. Pelajar yang bersemangat turun ke arena, menghadirkan kembali potongan sejarah tentang bagaimana sebuah kota—dulu bernama Batavia, kini Jakarta—didirikan arus manusia yang datang dari delapan arah mata angin.
Dari pertemuan suku Jawa dan Bugis, Sunda dan Minang, Aceh dan Melayu, Arab dan Tionghoa, Portugis dan Belanda, lahirlah satu identitas baru: Betawi. Sebuah etnik yang tidak lahir dari satu akar tunggal, tetapi dari simpul-simpul yang saling terikat. Dari situlah kita belajar bahwa menjadi Betawi berarti menjadi terbiasa dengan kemajemukan.
Orang Betawi dari sononya emang udah biasa campur sama bangsa mane-mane. Mereka terbiasa dengan bahasa campuran, ragam dialek yang terbentuk agar semua orang—pendatang dan tuan rumah—bisa saling mengerti. Dari pasar yang riuh sampai pelabuhan yang tidak pernah tidur, dari obrolan santai di Balekambang sampai ngariung di teras rumah, orang Betawi biasa ngobrol tanpa pandang bulu. Itulah sebab Betawi sejak awal ialah wajah keterbukaan.
Jakarta hari ini ialah cermin dari keterbukaan itu. Kota ini menerima siapa saja yang datang, tanpa menanyakan dari rahim mana ia dilahirkan. Betawi ialah rumah yang pintunya tak pernah tertutup. Lihatlah Benyamin Suaeb yang ayahnya dari Purworejo, atau saya—Rano Karno—yang dialiri darah Minang dari garis bapak; keduanya tumbuh dan lebur tanpa sekat dalam identitas Betawi.
Begitu pula mantan Gubernur Sutiyoso yang disapa akrab sebagai Bang Yos, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung yang kini dipanggil Bang Anung. Semua itu ialah refleksi bahwa Betawi bukan pagar, melainkan pelataran—bahwa Jakarta menyambut semua yang datang. Bagi siapa pun yang tulus hidup di dalamnya, kota ini akan memberikan nama belakang yang sama: Betawi.
Teater itu mengingatkan: sejak mula, Jakarta ialah melting pot. Ia ruang pertemuan, tempat manusia dari berbagai latar datang untuk tinggal, bekerja, dan merajut nasib.
Sejarah bangsa ini pernah menemukan momentum puncaknya di ruang lain, hampir satu abad lalu. Di sebuah rumah di Jalan Kramat 106, puluhan pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka datang bukan untuk pelesiran, melainkan untuk menuliskan sebuah janji, membulatkan sebuah tekad.
Tiga kalimat sederhana—satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—menjadi fondasi bagi Indonesia.
Di antara nama yang kerap disebut dalam buku-buku—Soegondo Djojopoespito, Muhammad Yamin, WR Supratman—ada nama lain yang jarang kita dengar: Mohammad Rochjani Soe’oed. Anak Betawi kelahiran Batavia, lulusan ilmu hukum, yang terpilih jadi panitia Kongres Pemuda II. Ia menjabat sekretaris pembantu V, dan memimpin jalannya sidang pada hari kedua.
Di Museum Sumpah Pemuda, patung miniaturnya berdiri. Sebuah pengakuan kecil bahwa sejarah pernah mencatat peran besarnya meski suara publik sering kali melupakan. Rochjani ialah representasi khas watak orang Betawi: tidak gemar menonjolkan diri, enggak suka pamer, tapi selalu hadir di tengah pusaran yang menentukan.
Selepas kongres, Rochjani tidak memilih panggung politik. Ia tidak berorasi seperti Yamin, tidak menulis lagu seperti Supratman, tidak juga menjadi ketua partai. Ia memilih jalan sunyi: menjadi hakim, menegakkan keadilan, menolak suap, hidup sederhana di rumah istrinya di Kemayoran. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi justru dari situlah ia dikenang kuat. Integritasnya menjadi warisan, lebih keras daripada orasi politik mana pun.
Dalam dirinya, kita menemukan sebuah ironi: bahwa seorang tokoh bisa memainkan peran penting dalam sebuah peristiwa besar, lalu memilih untuk kembali menjadi anonim. Sejarah Indonesia kerap menyanjung nama-nama yang lantang, tetapi melupakan mereka yang memilih diam, yang mengabdikan diri pada keadilan tanpa sorotan.
Apa arti semua ini bagi kita hari ini?
Mungkin jawabannya ada pada Batavia Ethnica. Teater yang dimainkan pelajar-pelajar Kanisius itu bukan sekadar tontonan. Ia pengingat bahwa Jakarta, serupa dengan Betawi, dibentuk dari keragaman yang riuh.
Rochjani Soe’oed, dengan kehadirannya yang senyap tapi berarti, ialah cermin orang Betawi: inklusif, terbuka, tapi tetap teguh memegang nilai. Ia hadir di tengah pusaran perdebatan pemuda 1928, ikut merumuskan sumpah yang mengajak bersatu, lalu kembali ke kehidupannya sehari-hari tanpa menuntut tepuk tangan dan sorot kamera.
Di situ kita belajar: nasionalisme tidak selalu lahir dari podium. Ia bisa lahir dari ruang sidang pengadilan, dari integritas menolak suap, dari kepiawaian memimpin sidang, dari hidup sederhana di rumah kecil. Nasionalisme bisa hadir dalam diam—“Kerja kite yang bener aje udah jadi ladang pahala, sudah jadi berkah,” begitu kata nasihat tetua kampung.
Jakarta hari ini masih memikul peran yang sama: episentrum. Kota ini tetap menjadi magnet. Orang datang dari Aceh hingga Papua, dari desa kecil hingga kota besar, dari benua lain, untuk menjemput nasib. Di terminal bus, di stasiun kereta, di bandara, kita bisa melihat wajah-wajah penuh harap, seperti dulu pemuda-pemuda itu datang ke Batavia dengan mimpi.
Namun, menjadi episentrum berarti juga menghadapi tantangan. Jakarta harus terus menjaga agar kebinekaan tidak berubah menjadi sekat. Agar keberagaman tidak terperangkap dalam prasangka yang sewaktu-waktu bisa membakar.
Masa depan Jakarta akan ditentukan sejauh mana kota ini bisa merawat semangat sebuah sumpah. Semangat bahwa 'kita satu' meski berbeda. Bahwa bahasa bisa menyatukan, bukan memisahkan. Bahwa tanah air ini ialah milik bersama, bukan milik segelintir.
Dalam riuh demonstrasi di jalanan, dalam perdebatan politik yang sering bising, kita sering lupa bahwa sumpah itu masih menunggu untuk dijalankan. Ia bukan sekadar upacara tahunan. Ia adalah tuntutan sehari-hari: di pasar, di sekolah, di kantor, di media sosial.
Jakarta ialah panggung tempat sumpah itu akan terus diuji. Jika Jakarta gagal merayakan kemajemukan, Indonesia bisa ikut rapuh.
Kita bisa membayangkan, andai Rochjani Soe’oed hadir di tengah kita hari ini, mungkin ia akan tersenyum getir. Ia akan melihat sumpah yang pernah ia jaga kini diperdebatkan dalam nada tinggi, tapi jarang dijalani dalam kebiasaan sehari-hari. Ia akan melihat kota yang tumbuh modern, tapi masih dihantui sekat-sekat kecil: etnik, ras, agama, kepentingan politik.
Namun, pada saat sama, mungkin ia juga melihat harapan. Dalam teater siswa Kanisius, ia menyimak 500 anak muda yang rela bangun pagi, berlatih berminggu-minggu, hanya untuk memainkan sejarah bangsa mereka, menceritakan perjalanan moyang mereka. Ia akan melihat bahwa sumpah itu, meski sering dilupakan, masih hidup dalam generasi baru.
Sejarah, demikian sering disampaikan, ialah cara kita becermin. Rochjani Soe’oed ialah cermin yang jernih. Ia mengingatkan bahwa sumpah ialah janji yang tidak selesai diucapkan, tetapi harus dijalani.
Jakarta ialah kaca besar tempat kita becermin bersama. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa hingga gedung pencakar langit Sudirman, dari kampung-kampung padat hingga pusat belanja modern, kota ini selalu menampung perbedaan, bijak bertenggang.
Seperti teater Batavia Ethnica, Jakarta ialah panggung. Kadang riuh, kadang muram. Namun, ia selalu menjadi tempat orang datang, tinggal, dan meninggalkan jejak.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda bukan cuma milik 1928. Ia milik kita hari ini. Ia janji yang masih bergaung di jalan-jalan Jakarta. Di bawah langit kota yang jingga menjelang senja, sumpah itu berbisik lagi: bahwa kita, putra dan putri Indonesia, telah berjanji. Janji yang tak boleh dikhianati meski waktu berjalan, meski kota berubah.
Jakarta, dengan segala riuh dan getirnya, akan selalu menjadi tempat janji itu diuji. Selama kita masih percaya pada janji itu, bangsa ini akan tetap berdiri.

 10 hours ago
5
10 hours ago
5













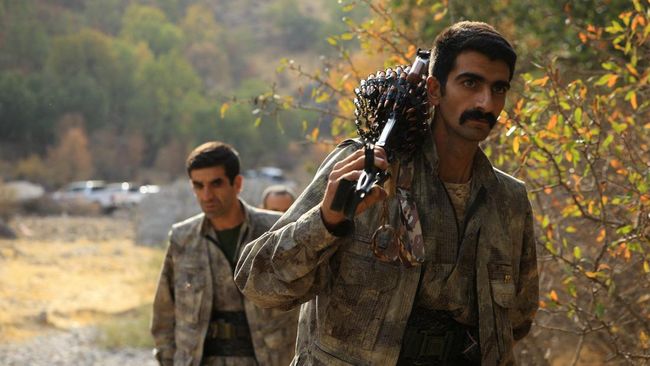







:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4712422/original/082274000_1704936798-000_343E9UQ.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5355398/original/029576100_1758298977-WhatsApp_Image_2025-09-19_at_22.50.23_f76b1b1f.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5353956/original/040562600_1758186528-Thumbnail_SCTV_Infotainment_Awards_2025.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3515744/original/041629600_1626769193-000_ARP4069963.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3240237/original/048246700_1600303636-ps5-04.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4677184/original/009841400_1701920967-Screenshot_2023-12-07_103353.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5355264/original/056678900_1758281471-WhatsApp_Image_2025-09-19_at_17.32.03.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1531926/original/069009300_1489055847-Nafa-Urbach-6.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5333528/original/078029600_1756646756-WhatsApp_Image_2025-08-31_at_15.18.12.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5141379/original/090135400_1740362319-Mohan_2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5352893/original/071452900_1758145788-AP25260730474674.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5348808/original/094973100_1757900938-Raisa_Marie_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5333603/original/084951800_1756676375-rayo_vs_barcelona_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5343768/original/082983900_1757472213-063_2210940745.jpg)
