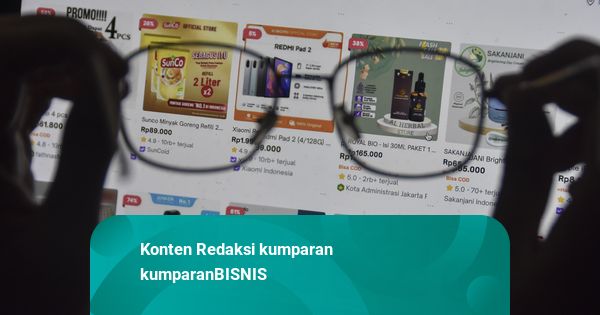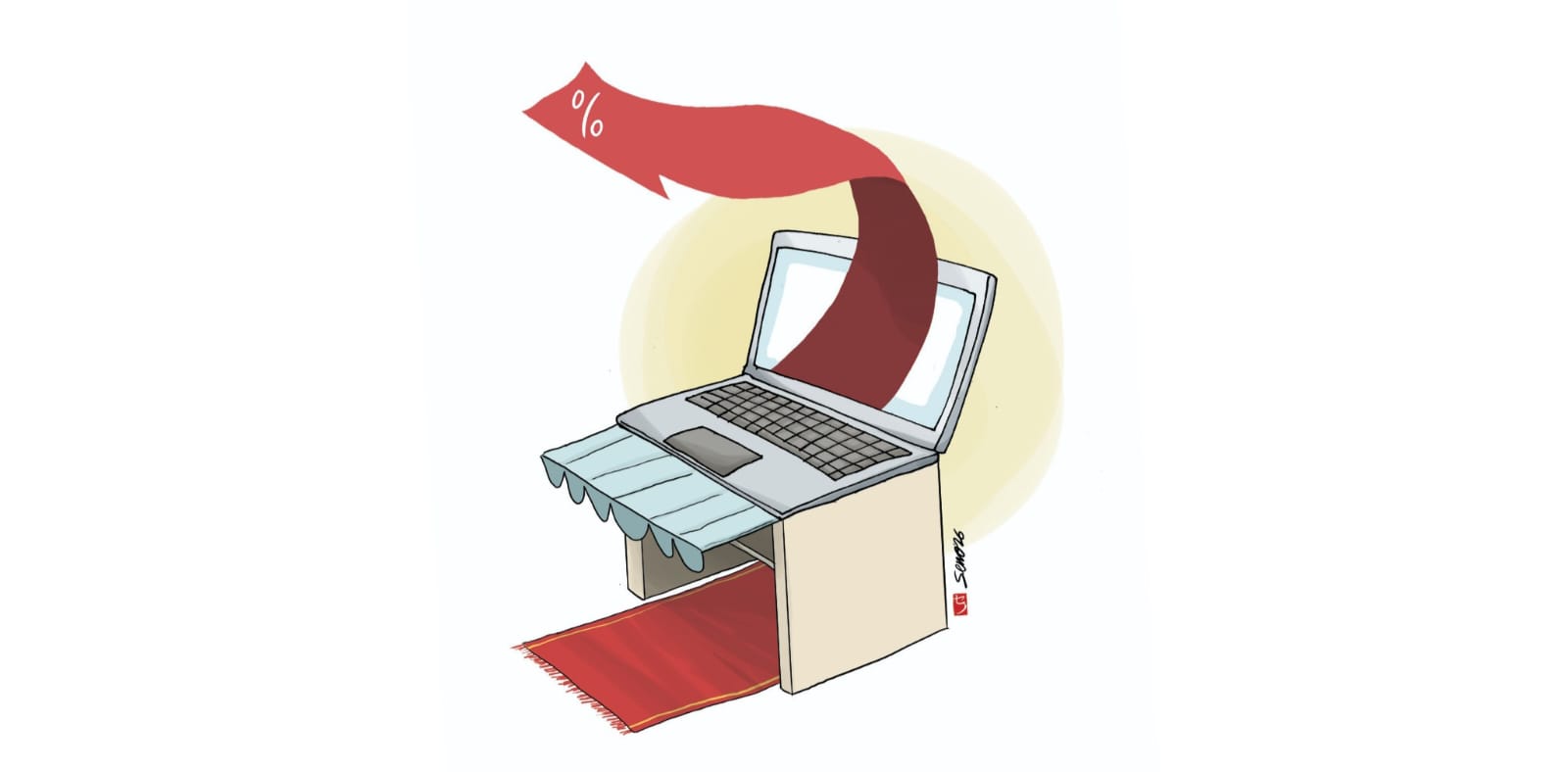(MI/Seno )
(MI/Seno )
ADA dua artikel yang ditulis Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner dalam dua tahun berturut-turut: 1976 dan 1977. Pada 1976, Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner, menulis satu artikel penting terkait bencana, Taking the Naturalness Out of Natural Disasters, (Nature, 260, 1976). Pada 1977, Ben Wisner, Phil O’Keefe, dan Ken Westgate menulis artikel lainnya, Global Systems and Local Disasters: The Untapped Power of Peoples’ Science (Disasters, 1[1], 1977). Ketika artikel ini dipublikasikan, ketiganya berkhidmat di The Institute of Development Studies University of Sussex, Kota Falmer, selatan Inggris.
Dalam artikel pertama, mereka yakin bahwa bencana lebih merupakan konsekuensi dari faktor sosial-ekonomi daripada faktor 'kealamiahan' alam. Dari judul artikel, substansinya bisa ditebak. Soal bagaimana tentang anggapan-pemikiran-konsep 'bencana alam' yang digunakan para ahli bencana sudah dikritisi sejak setengah abad yang lalu.
Artikel kedua mengulas informasi yang detail dan penting yang tersimpan dalam persepsi masyarakat lokal belum dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan pencegahan bencana. Soal mitigasi yang harusnya menjadikan pengalaman yang tersimpan dalam persepsi masyarakat lokal belum dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi pemangku kepentingan utama.
Pada saat itu, Indonesia memang sudah mengenal penanganan bencana walau dengan konsep yang masih terbatas. Konsep itu pun dalam hukum dan kebijakan kemudian berubah, menjadi penanggulangan bencana. Jika dibandingkan dengan daya pikir yang sudah muncul di banyak negara, perkembangan konsep dan praktik penanggulangan bencana sudah jauh dari apa yang masih menjadi panduan praktis di negara ini.
Jika merujuk pada perkembangan penanganan bencana, negara kita jauh tertinggal walau secara geografis berada dalam jalur cincin api (ring of fire). Sejak awal merdeka, para the founding father sempat berpikir tentang suatu badan yang yang akan menangani korban perang. Lembaga itu sendiri fokus pada situasi perang setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya.
Struktur baru mulai terbangun pada 1966 dengan nama Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP). Penanggung jawab lembaga itu ialah menteri sosial. Pada era itu, bencana masih terbatas pada cara berpikir tanggap darurat. Cara berpikir seperti itu bertahan hingga 1990. Waktu itu, mulai terbangun konsep bencana yang lebih luas, dengan membentuk Badan Koordinasi Nasional Panggulangan Bencana (Bakornas PB) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990. Bencana tidak terbatas pada bencana alam, tetapi sudah dikenal bencana nonalam dan bencana sosial.
Setelah reformasi, struktur dalam penanggulangan bencana berubah, dengan dibentuk Badan Koordinasi Nasional Panggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001. Hal yang berbeda, selain pada upaya peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana, muncul konsep bencana sosial, seiring dengan sejumlah konflik sosial yang muncul dalam era itu.
Tsunami Aceh 2004 mengubah cara pandang bangsa ini terhadap bencana. Lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Paradigma bencana tidak bertumpu pada tanggap darurat, tetapi pada aktivitas prabencana dan pemberdayaan pascabencana. Penanggulangan tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga pada masyarakat. UU itu memperluas cara pandang terhadap bencana sekaligus mengamanahkan satu badan penanggulangan bencana nasional.
Posisi badan yang disebut terakhir menjadi salah satu hal yang tidak tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif saat UU Penanggulangan Bencana mau dilakukan revisi. Proses tersebut terhenti dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan.
BUKAN KEALAMIAHAN
Walau sudah diatur dalam undang-undang, ternyata dalam praktik, cara pandang terhadap bencana juga belum banyak berubah. Umumnya, pemangku kepentingan mengaitkan bencana sebagai bencana alam. Hal itu tampak dalam ragam kebijakan penanggulangan bencana dan putusan hukum terhadap kasus yang terjadi. Dalam kasus kebakaran hutan dan dampak pertambangan, nyaris tidak banyak pertanggungjawaban yang harus ditanggulangi pelaku.
Padahal, artikel O’Keefe, Westgate, dan Wisner setengah abad yang lalu sudah terlalu kuat menyebut bahwa tidak semua bencana dapat dikategorikan sebagai bencana alam. Dengan kata-kata yang soft, mereka meminta pemikiran ulang terhadap kategori itu.
Hal lainnya yang disebutkan terkait dengan frekuensi bencana alam yang semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Ia menyebut kondisi negara-negara tersebut dalam posisi yang sedang membangun, menyebabkan dampak, dan itu tidak bisa dianggap semata soal bencana yang 'alami'.
Sepertinya perbedaan cara pandang itu yang terjadi setelah bencana yang melanda Sumatra, sejak 25 November 2025. Bencana itu diperdebatkan apakah ia masuk kategori bencana alam atau bencana ekologis. Secara konsep, pilihan bencana alam sangat terasa. Implikasinya tentu saja kepada proses pertanggungjawaban yang harusnya tidak sederhana. Namun, ada catatan menarik yang dilakukan institusi pemerintah, yakni penegak hukum yang melakukan sejumlah upaya hukum (ranah pidana), atau pencabutan izin tertentu (ranah administrasi negara), dan gugatan ganti rugi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai Rp4,8 triliun (ranah perdata). Apa yang dilakukan pemerintah pada dasarnya ada pengakuan terhadap bencana ekologis yang terjadi dua bulan yang lalu itu.
Sudut pandang dalam praktik itu sesungguhnya juga bukan terjadi dengan sendirinya. Basis pikir yang dirumuskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana yang disiapkan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat pada 2005, kelak RUU itu menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mencerminkan bagaimana kuatnya cara pandang bencana nonalam di negara ini.
Naskah akademik yang disusun merujuk pada model klasifikasi bencana ke dalam dua jenis, yakni bencana alam (natural disaster) yang disebabkan kejadian alam (natural) seperti gempa bumi dan gunung meletus; dan bencana buatan manusia (man-made disasters), yaitu hasil dari tindakan secara langsung atau tidak langsung manusia (DPR, 2005).
Man-made disasters sesungguhnya bisa sangat luas, termasuk perang, terorisme, kecelakaan industri, bahkan kebakaran hutan, dan dapat saling memicu: manusia memicu alam atau sebaliknya. Atas dasar itulah, siklon senyar akhir November tahun lalu tidak bisa dijadikan dalih untuk kejahatan bencana. Siklon senyar yang bahkan sudah diingatkan sejumlah ahli untuk menyiapkan mitigasi. Ia sebagai 'bencana dari awan', tetapi sangat ditentukan bagaimana kesiapan 'bencana darat'.
Jadi, semua pihak jangan menyembunyikan manusianya. Pikiran seorang sosiolog bencana, Carr (1932) yang dikutip ahli kebijakan iklim Filipina, Emmanuel de Guzman (2005), barangkali dapat menjadi catatan penutup. Ia menyebutkan, “Not even windstorm, earth-tremor, or rush of water is a catastrophe. A catastrophe is known by its works; that is, to say, by the occurrence of disaster. So long as the ship rides out the storm, so long as the city resists the earth-shocks, so long as the levees hold, there is no disaster. It is the collapse of the cultural protections that constitutes the disaster proper.”
Jika diterjemahkan secara bebas, “Bahkan badai angin, gempa bumi, atau derasnya air bukanlah bencana. Bencana dikenal dari perbuatannya, yaitu dari terjadinya bencana. Selama kapal mampu melewati badai, selama kota mampu menahan guncangan bumi, selama tanggul bertahan, tidak ada bencana. Runtuhnya perlindungan budaya itulah yang merupakan bencana sesungguhnya.”

 2 hours ago
2
2 hours ago
2